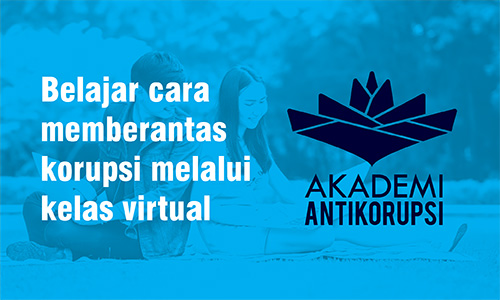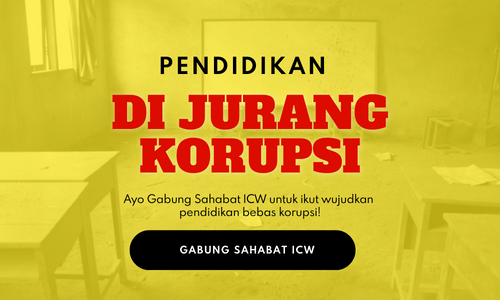Korupsi: Upaya Membunuh Demokrasi dan Hak Asasi
“Korupsi punya andil besar dalam merampas hak hidup orang. Ia merampas begitu banyak kemampuan untuk melayani kehidupan masyarakat.” Demikian tegas Mas Alvin dari Transparency International Indonesia (TII) pada kuliah umum yang saya ikuti. Ia mengingatkan saya pada destruktifnya daya rusak di balik tindak korupsi. Saya menyadari bahwa korupsi menghasilkan monetary loss. Akan tetapi, masih sering luput dari perhatian masyarakat bahwa korupsi juga melahap “ongkos” kerugian lain yang bisa dieksplorasi lebih jauh, khususnya kerugian sosial yang merenggut pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Ada orang-orang yang terancam kehidupannya ketika bantuan di masa darurat pandemi Covid-19 malah dikorupsi untuk menyuapi perut-perut pejabat yang tak pernah mengenal kenyang. Ada hak atas penegakan keadilan yang dilanggar saat nyawa seorang perempuan “dibayar” pelaku sebagai harga untuk membeli impunitas. Ada gratifikasi seksual yang belum dinaungi payung hukum dan berpotensi jadi praktik eksploitasi tanpa bisa dijerat secara legal. Ada anak-anak yang direnggut haknya atas pendidikan karena kualitas sekolah banyak diperas habis oleh praktik-praktik koruptif, dan masih begitu panjang realitas penderitaan rakyat di balik gelontoran dana korupsi yang dinikmati para pemegang tampuk kekuasaan.
Namun, bukan tanpa alasan korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Para pelakunya tak hanya merugikan rakyat, tetapi juga ada unsur abuse of power, penyalahgunaan instrumen birokrasi untuk kepentingannya sendiri, yang kemudian menebalkan wajah impunitas di muka bumi Indonesia, mengkhianati peran negara itu sendiri sebagai duty-bearer dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya.
Menjadi suatu urgensi untuk lekas menguak borok permasalahan korupsi di Indonesia, mulai dari pendefinisiannya yang masih usang jika dibandingkan di level global ataupun dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju, terbatasnya “topik” korupsi pada monetary loss di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, minimnya cakupan aktor-aktor yang dapat dijerat, serta lemahnya pendefinisian harta kekayaan yang tidak sah.
Sesuai teori rational choice, pelaku korupsi memang amat diuntungkan. Dengan lemahnya penegakan hukum, korupsi hanya menempatkan pelaku sesaat di tempat yang katanya penjara (tetapi tentu berbeda “level”-nya dengan penjara bagi masyarakat kelas menengah ke bawah), untuk kemudian bisa mewariskan harta kekayaan bagi tujuh generasi keturunan karena perampasan aset tidak berjalan. Belum lagi mempertimbangkan kekuasaan mereka untuk “mengakses” perumusan kebijakan yang memungkinkan adanya undang-undang pesanan sebagai bentuk political corruption, tetapi tidak bisa dipidana karena sistem hukum Indonesia belum mengenal (atau memang pura-pura tak mengenali) jenis korupsi tersebut.
Korupsi sudah seharusnya diakui sebagai bentuk pelanggaran HAM, sebagaimana dikemukakan data TII bahwa di negara yang cenderung korup (Corruption Perception Index-nya tinggi), pemenuhan hak warga negaranya juga cenderung buruk. Di negara korup, upaya untuk melindungi warga negaranya cenderung rendah. Oleh karena itu, korupsi merusak demokrasi, berdampak buruk pada supremasi hukum (padahal supremasi hukum merupakan instrumen penegakan HAM), merusak kepercayaan publik, sekaligus mendistorsi kemampuan negara dalam melayani publik demi mencapai margin keuntungan untuk kepentingannya sendiri.
Dengan demikian, negara perlu bergegas mengakui korban korupsi dalam peraturan perundang-undangan, serta memperkuat pendekatan victim-centered dan human rights-based, apalagi jika mempertimbangkan temuan Global Corruption Barometer bahwa kelompok marginal lebih rentan terkena dampak korupsi dalam layanan dasar. Momen monumental yang pernah terekam dalam sejarah Indonesia adalah solidaritas 18 orang yang pertama kalinya mengajukan gugatan ganti rugi pada 2021 sebagai korban tindak pidana korupsi. Mereka berhasil mendobrak keterbatasan hukum Indonesia yang selama ini tak mengenal “korban korupsi”, mengingat korupsi dianggap sebagai victimless crime.
Dalam buku Kriminologi Syariah, saya menemukan bahwa strategi memberantas korupsi telah banyak diajukan ahli, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, dengan strategi Carrot and Stick. Prinsipnya: sejahterakan pejabat, baru tegakkan hukum secara tegas bagi koruptor, dengan asumsi bahwa korupsi disebabkan ketidakadilan pemberian gaji dan ketidakseimbangan beban tanggung jawab dengan gaji.
Namun, saya sadari bahwa peningkatan gaji justru menambah problematika, seperti kecemburuan sosial, kesenjangan antara pegawai negeri dengan masyarakat umum, konflik kepentingan antara yang bergaji tinggi dengan yang rendah, pembengkakan beban negara, dan yang paling penting, pemberantasan korupsi sendiri belum bisa dipastikan. Hal ini dapat kita saksikan pula pada melambungnya tunjangan wakil rakyat yang memicu masyarakat untuk turun tangan mengimplementasikan “perampasan aset” secara langsung pada beberapa waktu terakhir.
Sebagai pelanggaran HAM, korupsi perlu ditindak dan diberi atensi lebih karena praktiknya menabrak hak-hak warga negara. Gara-gara tindak korupsi, ada sosok yang kehilangan hak untuk mengakses keadilan, layanan pendidikan, lingkungan yang aman, maupun hak-hak dasar lainnya. Gara-gara tindak korupsi, impunitas di dalam negeri tak akan pernah basi.
Penulis,
Naswa Dwidayanti Khairunnisa
Mahasiswi Kriminologi Universitas Indonesia
*Artikel Sayembara Opini Antikorupsi September 2025